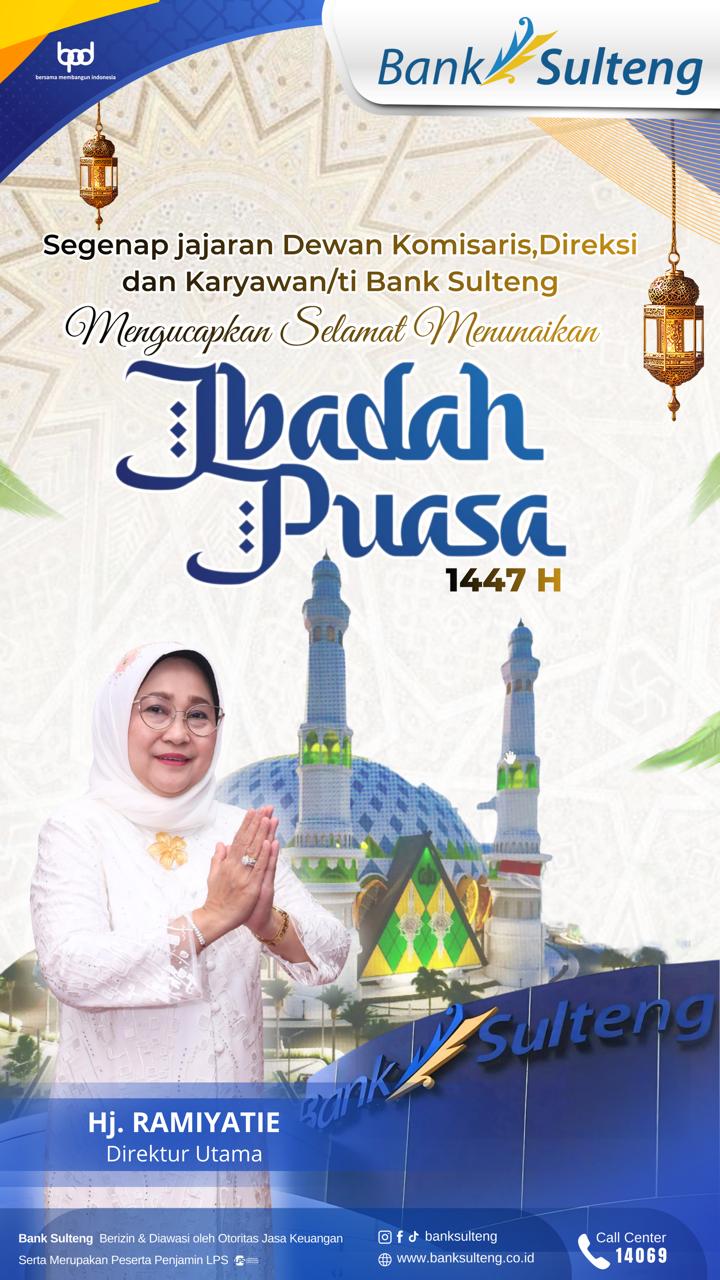ramai diperbincangkan. Pemicunya adalah perkataan Prabowo Subianto saat
meresmikan Kantor Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi pada Selasa
(30/10/2018). Prabowo dianggap menghina dan melecehkan orang
Boyolali yang ia sebut tak pernah masuk hotel-hotel mewah karena wajahnya tak
mendukung.
kalau kalian masuk mungkin diusir karena tampang kalian tidak tampang orang
kaya. Tampang kalian ya tampang Boyolali,” ucapnya.
menyampaikan bahwa dirinya ingin berjuang untuk rakyat kecil yang ia sebut
sebagai “tampang Boyolali yang tak pernah masuk hotel-hotel mewah” itu.
apa saya berjuang? Apakah saya berjuang supaya negara kita bisa jadi milik
orang asing? Saya tidak rela. Saya lihat rakyat saya masih banyak yang tidak
dapat keadilan dan tidak dapat kemakmuran, dan tidak dapat kesejahteraan,”
imbuhnya.
Boyolali” tentu tak menimbulkan kemarahan, hadirin malah menyambutnya dengan
tawa. Terlebih karena ia selanjutnya menyatakan keberpihakannya kepada rakyat
kecil.
bagi Prabowo. Calon presiden nomor urut dua itu menuai kritikan bahkan unjuk
rasa. Jejaring media sosial dengan cepat menyebarkan ucapannya laksana sampar.
Harimau yang mengeram di mulut, berbalik menerkamnya. Satu lagi tokoh politik
nasional menuai badai dari angin yang ditaburnya.
ingatan masyarakat bagaimana Jokowi yang berucap “politikus sontoloyo” juga
mendapat tanggapan yang beragam. Selain itu, ada pula Koordinator Juru Bicara
Prabowo-Sandi, Dahnil Azhar Simanjuntak, yang mengibaratkan Sandiaga Uno
sebagai Bung Hatta. Ucapannya kontan diprotes Gustika Jusuf Hatta, salah
seorang cucu proklamator tersebut.
Yang paling fenomenal soal buang abab tokoh politik di muka publik dan mendapat
kecaman tentu Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ia yang saat itu menjabat
sebagai Gubernur Jakarta diserbu ribuan pengunjuk rasa yang datang berulang
memenuhi ruas jalan-jalan ibukota. Ahok malah diseret ke meja hijau dan
akhirnya menghuni hotel prodeo.
“Boyolali”
pelbagai daerah di Indonesia, dari dulu berkembang tradisi lisan. Kisah-kisah
didongengkan dari ke mulut ke mulut. Tingkat presisi sebuah cerita menjadi
variatif, kadang menggembung kadang mengempis. Peristiwa mewujud cerita yang
akhirnya sampai pada generasi kiwari dengan pelbagai penambahan atau
pengurangan dari aslinya. Ada toleransi yang menyertai bahwa lisan rentan alpa
dan silap.
atau cerita rakyat. Dalam konteks Boyolali yang tengah “panas” akibat ucapan
Prabowo, juga lahir beberapa sastra lisan yang salah satunya adalah tentang
asal mula nama kota tersebut.
kekayaan berlimpah. Harta bendanya membuat ia sombong dan melupakan ibadah.
Para wali penyebar Islam di Pulau Jawa mengetahui hal itu dan mengutus Sunan Kalijaga
untuk menginsafkannya.
penjual rumput. Ki Ageng Pandanarang membelinya dengan harga murah. Namun ia
heran, sebab di dalam ikatan rumput tersebut terselip sebilah keris berpamor
indah dan terbuat dari emas. Sunan Kalijaga tengah mengujinya.
tinggalnya dipugar. Ia mengundang seluruh bupati yang berkuasa di sepanjang
pesisir pantai utara Jawa. Dalam acara itu, Sunan Kalijaga datang kembali, kali
ini menyamar sebagai rakyat jelata. Ki Ageng Pandanarang tak menghiraukan. Ia
menganggapnya hanya rakyat biasa yang hendak numpang makan.
pakaian dengan yang lebih bagus dan mewah. Ia lalu disambut oleh sang bupati
dan diajak berkeliling melihat tempat tinggalnya. Semua bupati memuji, sementara
Sunan Kalijaga menyindirnya.
indah dan megah, tapi sayang keindahan dan kemegahan istana itu membuat orang
lupa daratan. Ki Ageng Pandanarang tidak merasa tersinggung oleh ucapan itu.
Sunan Kalijaga sangat kecewa, namun ia tidak berputus asa,” tulis Mardiyanto
dalam Cerita Rakyat Kabupaten Boyolali: Transkripsi dan Terjemahan (2005).
mendatangi Ki Ageng Pandanarang yang tengah menghitung uang di pendopo
kabupaten. Sang bupati memberinya uang, tapi si pengemis menolak. Pengemis itu
berkata bahwa dirinya tak menghendaki uang, melainkan meminta agar bupati
menghidupkan agama dan tak lena dengan kekayaan. Permintaannya itu tentu saja
ditolak. Sunan Kalijaga yang tengah menyamar lalu mencangkul tanah dan tanah
itu berubah menjadi emas.
ia akhirnya menyadari bahwa dirinya selama ini diuji melalui pelbagai
perlambang dan kiasan. Ia lalu hendak berguru kepada pengemis itu. Setelah
didesak bupati, pengemis mengaku dirinya bernama Seh Malaya.
bupati untuk menerimanya sebagai murid dengan tiga syarat. Pertama, Ki Ageng
Pandanarang harus beribadah dan mendirikan langgar. Kedua, harus mengeluarkan
zakat. Dan ketiga, harus meninggalkan Semarang dan tinggal di Jabalkat di
daerah Tembayat.
dua syarat pertama, ia lalu berangkat menuju Tembayat beserta istri dan anak
bungsunya. Dalam perjalanan mereka dirampok, tapi akhirnya perampok tersebut
menjadi pengikutnya.
anak, dan dua pengikutnya jauh tertinggal. Saat istrinya tiba di sungai
Tempuran lalu wudu dan duduk di atas sebuah batu datar tempat yang digunakan
suaminya untuk salat sebelum ia datang ia melihat ke depan dan suaminya tak
tampak.
sehingga meninggalkan aku),” gumamnya seperti ditulis Mardiyanto (2005).
Sementara dalam
laman resmi Pemerintah Kabupaten Boyolali,perkataan itu berbunyi, “Baya wis lali wong iki (Sudah lupakah orang
ini).”
Ucapan istri Ki Ageng Pandanarang tersebut kemudian terkenal dan
“Boyolali” dijadikan nama tempat itu.
salah satunya tentang tanah yang menjadi emas. Namun, tradisi lisan memang
menyediakan ruang untuk itu, dan masyarakat pun memakluminya.
Di titik ini, Boyolali sebagai cerita rakyat dan kegaduhan yang mencuatkan kota
tersebut menjadi perhatian orang ramai sama-sama terlahir dari buang abab.
Namun, ada perbedaan di zaman ini. Ucapan Prabowo tentang “tampang
Boyolali” tak diperlakukan sebagaimana masyarakat memahami sastra lisan.
Padahal, bukankah ucapan Prabowo itu bisa saja mempunyai salah satu ciri sastra
lisan sebagaimana kisah Ki Ageng Pandanarang, yakni di luar akal sehat.**