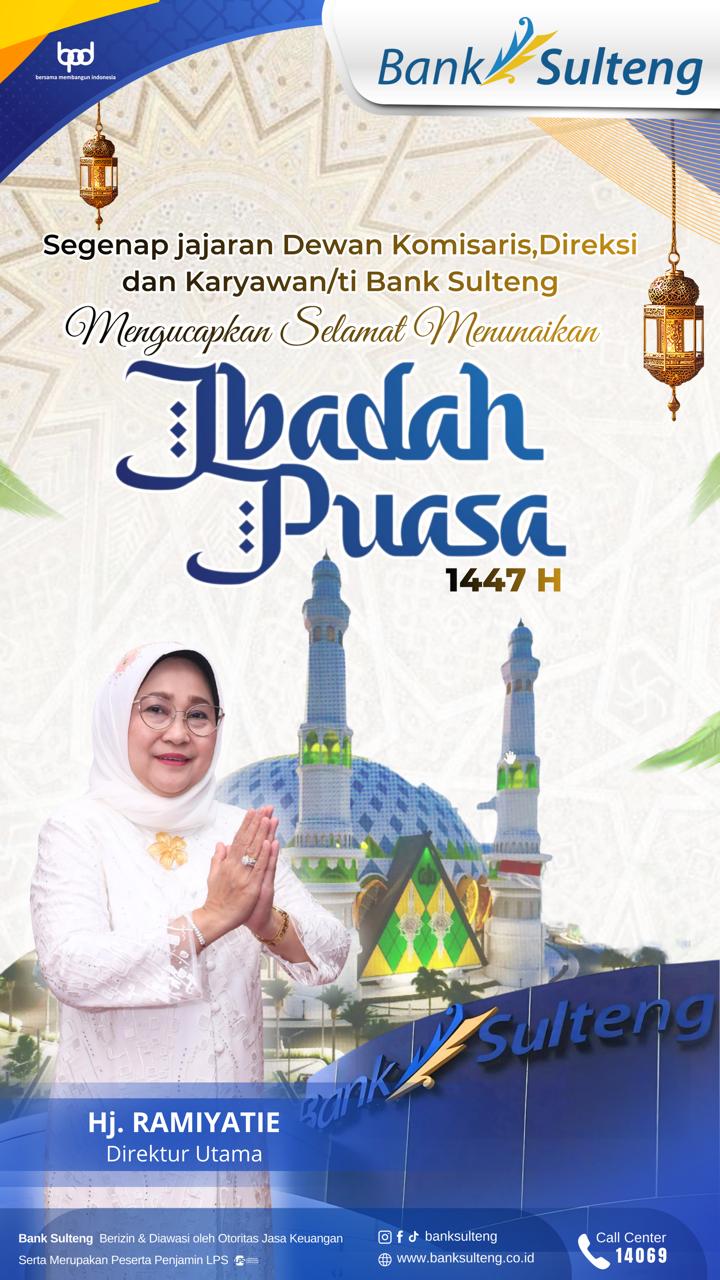Oleh: Hasanuddin Atjo
Dalam penerbangan Palu tujuan Makassar beberapa waktu lalu, saya duduk bersebelahan dengan seorang bapak setengah umur tujuan Jakarta dan transit di Sultan Hasanuddin Makassar. Protokol Covid-19 secara ketat diterapkan antara lain pakai masker dan jaga jarak dengan sengaja seat tengah dikosongkan, tidak ditempati.
Kurang dari 10 menit kemudian, sinyal lampu seat belt dan toilet berubah menjadi hijau, sebagai tanda bahwa ketinggian pesawat berada di titik normal sekitar 28 ribu kaki di atas permukaan laut. Crew maupun penumpang sudah diperkenankan melepas seat belt, menggunakan toilet, bahkan bisa ngobrol, berdialog karena deru mesin pesawat kembali normal.
Sesaat kemudian bapak di sebelah saya menyapa dan mengenalkan dirinya, menanyakan asal usul dan aktifitas keseharian sebagai etika pembicaraan dengan orang yang baru dikenal. Selanjutnya topik diskusi bergeser ke Pilkada tahun 2020. Rupanya yang bersangkutan seorang pelaku usaha di Jakarta yang ada urusan di Palu dan juga pengurus sebuah partai.
Dia bertanya ke saya, ada berapa calon yang akan ikut kontestasi pilgub Sulteng 2020 pak? Secara normatif saya menjawab bahwa syarat minimal untuk mengusung pasangan calon minimal 9 suara di DPRD, atau paling tidak pilgub di 2020 bisa mengusung 4 pasangan calon. Namun hingga saat ini baru satu pasang calon yang memenuhi syarat untuk itu.
Si bapak kembali bertanya kenapa begitu sulit menetapkan pasangan calon. Apalagi 3 September, tidak cukup satu bulan KPU membuka pendaftaran. Di daerah lain sejak lama sudah ada penetapan calon sambungnya. Secara diplomatis saya jawab mungkin komunikasi politik kurang terbangun dengan bagus sehingga terlambat tetapkan figur yang akan ikut berkontestasi. Mungkin bapak tersebut paham dengan yang saya maksud karena dia pengurus partai dan kemudian dia alihkan topik pembicaraan.
Kami kemudian ngobrol “ngalor-ngidul” dan tidak terasa pesawat akan landing.
Flashback atau kilas balik Pilgub di Sulawesi Tengah secara langsung, menunjukkan bahwa di tahun 2006 kandidat yang ikut berkontestasi mencapai 4 pasang. Di Pilkada 2011 meningkat menjadi 5 pasang. Ini memberikan indikasi tumbuhnya demokrasi. Selanjutnya di Pilkada 2016 anjlok menjadi 2 pasang. Dan di pilkada di tahun 2020 diprediksi oleh sejumlah kalangan maksimal 2 pasang, bahkan bisa jadi akan lawan kotak kosong, karena hingga saat ini baru satu pasang yang memenuhi syarat.
Berdasarkan Data Pilkada Sulteng di atas, ada kecenderungan jumlah kandidat yang ikut berkontestasi semakin menurun. Sejumlah orang menilai bahwa mahalnya cost atau mahar politik, dan ditambah biaya kampanye serta biaya lainnya yang semakin tinggi menjadi salah satu sebab berkurangnya peserta yang tertarik dan lolos sebagai peserta Pilkada. Ditambah dengan dugaan bahwa saat ini jumlah “sponsor” Pilkada jauh menurun, dibanding sebelumnya karena resesi ekonomi oleh Covid-19, serta ditariknya sejumlah kewenangan daerah antara lain pengelolaan minerba.
Sutuasi, kondisi seperti ini tentunya bisa menjadi preseden buruk bagi perkembangan berdemokrasi dan keterbukaan di Sulteng. Pertama, bagi warga negara yang memiliki “kualitas, integritas dan isi tas” tidak lagi tertarik ikut berkontestasi. Golongan ini lebih mengedepankan pertimbangan rasionalitas, bukan emosional untuk sekedar terpilih dan berkuasa.
Kedua, figur yang tampil semakin terbatas jumlahnya sehingga akan mengurangi pilihan masyarakat, dan dinilai berpotensi menurunkan tingkat partisipasi masyarakat dalam menyalurkan hak suaranya dan bermuara kepada menurunnya kualitas berdemokrasi. Padahal tujuan dari Pilkada langsung adalah meningkatkan kualitas demokrasi.
Ketiga, sulit diharapkan terjadinya perubahan yang signifikan karena masyarakat masih terperangkap dengan politik transaksional dan populeritas dari kandidat, sehingga kualitas dan integritas belum jadi sebuah kebutuhan. Sementara daerah ini membutuhkan pemimpin yang mampu membawa keluari dari sejumlah masalah yang dihadapi antara lain kapasitas fiskal kategori sangat rendah, mendekati 90 persen bergantung kepada APBN, serta angka kemiskinan, ketimpangan dan stunting yang masih tinggi di atas rata-rata nasional.
Mahalnya cost atau mahar politik di sejumlah Pilkada, telah menjadi perhatian Mendagri Tito Karnivian. Dalam satu kesempatan mendagri mengatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian untuk menjadi bupati membutuhkan cost sampai dengan Rp30 Milyar, kemudian gubernur costnya bisa mencapai Rp100 Milyar, bergantung kondisi daerahnya. Sementara itu pendapatan resmi seorang bupati Maksimal 2,4 miliar per tahun. Kalau seperti itu bagaimana cara mengembalikan biaya Pilkada itu. Tentunya pembaca yang paling tau jawabannya. Sementara itu hasil penelitian Indonesian Institut (2019) menunjukkan rata-rata kekayaan calon gubernur yang ikut kontestasi hanya sekitar Rp21 Milyar rupiah.
Karena itu menurut Tito diperlukan evaluasi terhadap pilkada langsung dan mempertimbangkan kembali pilkada tidak langsung melalui DPR.
Bahkan Tito menyarankan bila perlu di Pilkada 2020 dilakukan secara asimetris yang maksudnya daerah dengan kadar demokrasi tinggi bisa melakukan Pilkada langsung, sedangkan daerah dengan kadar demokrasi dianggap rendah dapat melakukan Pilkada tidak langsung melalui DPR.
Mengakhiri artikel ini tentunya semua berharap kiranya Pilkada Sulteng di 2020 bisa melahirkan minimal 2 pasang calon dan kalau memungkinkan bisa lebih dari 2 pasang. Selanjutnya di Pilkada di 2024 diharapkan ada perubahan paradigma pemilik hak usung dan pemilik hak suara agar kedepankan pertimbangan kualitas maupun integritas, mengingat tahun 2028 kita menghadapi bonus demografi yang sangat kental dengan nuansa digitalisasi, industri 4.0.
Bila paradigma hak usung belum berubah, maka peran masyarakat untuk mendukung calon dari jalur independen menjadi satu alternatif penting dan strategis. Kita berharap Pilkada di Sulteng tahun 2020 bisa menjadi momentum untuk menuju kepada Pilkada yang berkualitas. di tahun 2024. SEMOGA.***