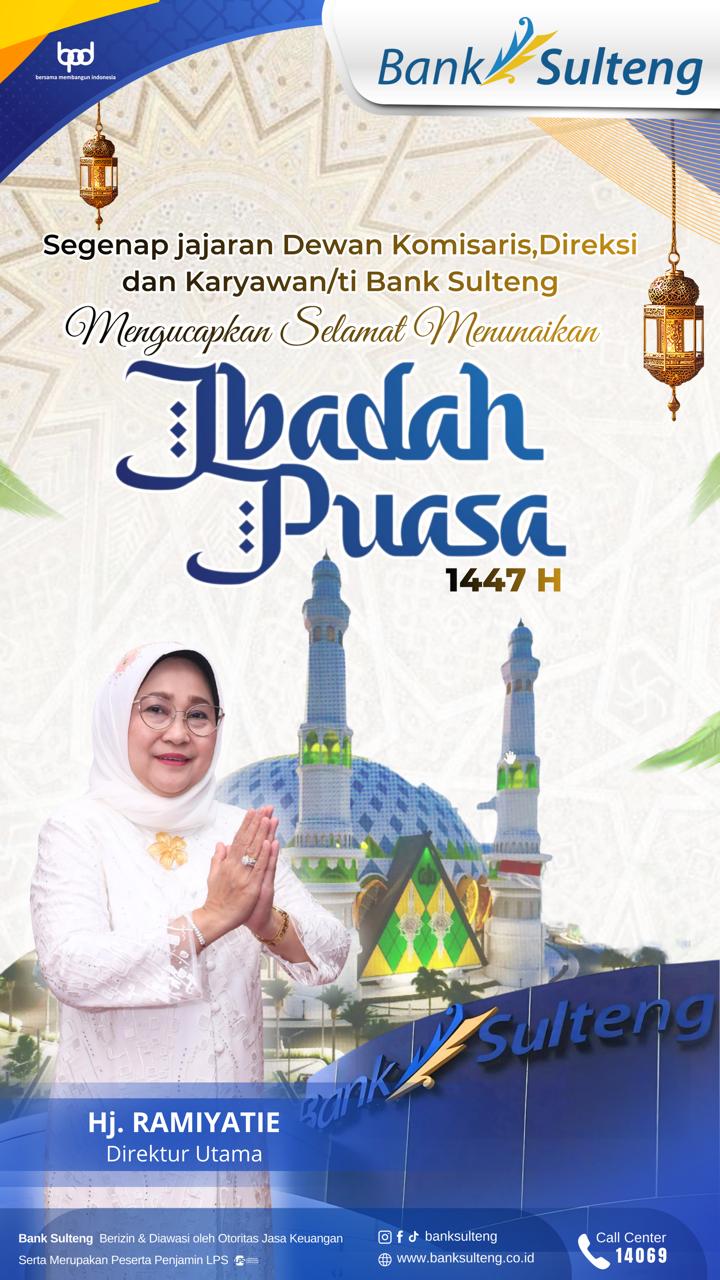Oleh : Ruslan Sangadji (Ahli Dewan Pers)
DI RUANG Redaksi media arus utama, kata malinformasi nyaris tak pernah terdengar. Bukan karena jurnalis tak mengenalnya, melainkan karena istilah itu seperti tak punya tempat hidup di dunia yang dibangun di atas verifikasi, disiplin fakta, dan tanggung jawab etik. Media arus utama tak lahir untuk bermain di wilayah abu-abu, tetapi berdiri di atas terang atau gelap: benar atau salah, hitam atau putih.
Malinformasi, dalam definisi akademik, adalah informasi yang benar secara fakta, tetapi disajikan dengan niat jahat: dipelintir konteksnya, disusun waktunya, atau diarahkan maknanya agar melukai pihak tertentu.
Tetapi Itu bukan hoaks, bukan pula disinformasi. Itu lebih licin, lebih halus, dan karena itu lebih berbahaya. Namun justru di sinilah perbedaannya: media arus utama tidak bekerja dengan niat jahat (kalimat ini harus dibold agar bisa dibaca lebih jelas).
Lazimnya, setiap berita di media arus utama, telah melewati pintu-pintu yang berlapis. Ada reporter yang mencatat, editor yang menguji, redaktur yang menimbang, hingga pemimpin redaksi yang bertanggung jawab. (Ini yang sering saya sampaikan ketika dimintai keterangan ahli pers di penyidik maupun di pengadilan).
Proses ini bukan ritual kosong. Tetapi sebagai pagar etika, yang memastikan informasi tidak hanya “benar”, tetapi juga “adil”. Fakta tak boleh berdiri telanjang tanpa konteks. Kutipan tak boleh dilepas dari maksud utuhnya. Data tak boleh dijahit untuk menggiring kesimpulan pesanan.
Lantaran itu, ketika sebuah berita dianggap “menyakiti”, media arus utama tidak serta-merta dituduh menyebar malinformasi. Yang diuji pertama kali adalah: apakah faktanya salah? Apakah konteksnya dipotong? Apakah ada niat untuk menyesatkan? Jika jawabannya tidak, maka yang terjadi bukan malinformasi, melainkan ketidaknyamanan pembaca terhadap kebenaran.
DIPAKAI SEBAGAI TAMENG
Di era media sosial, istilah malinformasi sering dipakai sebagai tameng. Itulah yang menjadi kata kunci untuk membungkam berita yang tak disukai. Ketika fakta terasa pahit, maka label pun ditempelkan. Padahal, rasa pahit bukan indikator kebohongan. Jurnalisme bukan obat penenang; tetapi cermin. Dan cermin tak pernah berdosa hanya karena memperlihatkan wajah yang kusut.
Media arus utama tentu tidak suci. Bisa juga keliru, dan karena itu mekanisme koreksi disediakan. Ada hak jawab, ralat, dan klarifikasi, adalah bukti bahwa jurnalisme bertanggung jawab. Kesalahan diakui, diperbaiki, dan diumumkan. Di situlah perbedaan mendasarnya dengan malinformasi yang bekerja diam-diam, menolak koreksi, dan hidup dari viralitas.
Maka, mengatakan ada “malinformasi” di media arus utama sesungguhnya adalah salah alamat. Yang ada adalah jurnalisme yang diuji publik, diuji waktu, dan diuji akal sehat. Media arus utama boleh dikritik, bahkan harus dikritik. Tetapi menuduhnya menyebar malinformasi sama dengan menuduh niat jahat pada sebuah kerja yang sejak awal dibangun untuk melayani kebenaran.
Di tengah kebisingan digital, media arus utama tetap memegang satu keyakinan tua: fakta bukan musuh siapa pun. Ia hanya tak pernah berpihak pada kepentingan yang ingin bersembunyi. (*)
Wallahu A’lam