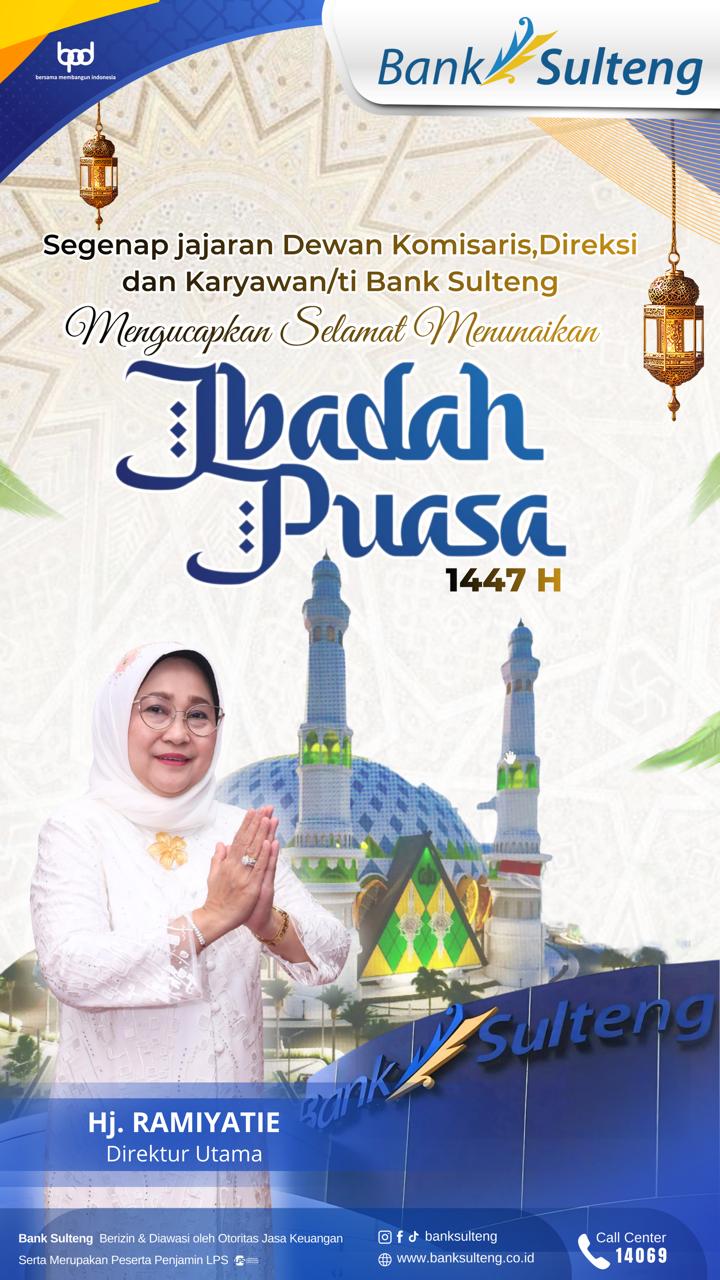OLEH : MUHARRAM NURDIN (Mahasiswa Program Doktor Ilmu Politik Unhas)
Apakah DPRD Sulawesi Tengah sedang diabaikan? Pertanyaan ini muncul bukan tanpa sebab, melainkan lahir dari rangkaian peristiwa yang sulit dianggap kebetulan. Dalam dua hari berturut-turut, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menghadapi kenyataan pahit, undangan resmi Rapat Dengar Pendapat (RDP) diabaikan oleh korporasi.
Komisi III DPRD Sulteng tidak dihadiri PT Citra Palu Mineral (CPM). Sehari sebelumnya, Panitia Khusus II DPRD yang ditugasi menyelesaikan konflik agraria dua perusahaan sawit di Kabupaten Tolitoli mengalami hal serupa. Ironisnya, ketidakhadiran itu disertai alasan yang mencengangkan: perusahaan “memiliki aturan sendiri”.
Jika alasan ini dibiarkan, maka persoalannya bukan lagi sekadar etika kelembagaan, melainkan tantangan terbuka terhadap kewenangan negara.
DPRD Bukan Lembaga Undangan Seremonial
Sesuai konstitusi dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD ditempatkan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, bukan sekadar pelengkap eksekutif. Fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD mencakup hak meminta keterangan dari setiap pihak yang terkait dengan kepentingan publik, termasuk korporasi.
Demikian juga sesuai perspektif teori negara hukum (Rechtsstaat), semua subjek hukum baik individu maupun badan usaha tunduk pada mekanisme pengawasan negara. Tidak ada ruang bagi “aturan internal perusahaan” untuk mengalahkan hukum publik. Izin usaha bukan hak alamiah, melainkan privilege administratif yang diberikan negara dan karenanya dapat diawasi, dievaluasi, bahkan dicabut.
Mangkir sebagai Bentuk Perlawanan terhadap Pengawasan
Ketidakhadiran berulang tanpa alasan sah dapat dibaca sebagai bentuk penghindaran akuntabilitas. Dalam teori administrative accountability, setiap pemegang izin wajib membuka diri terhadap pengawasan publik. Menolak hadir di DPRD sama artinya dengan menutup pintu pengawasan.
Di titik ini, narasi “penghinaan terhadap DPRD” sebenarnya terlalu lunak. Yang terjadi lebih serius pelemahan institusional terhadap fungsi pengawasan negara oleh kekuatan ekonomi.
Panggil Paksa dan Kekosongan Tata Tertib
Memang benar, Tata Tertib DPRD mengatur kewenangan pemanggilan paksa, namun tidak menjelaskan secara teknis mekanisme pelaksanaannya. Ini adalah contoh klasik kekosongan norma operasional. Namun, menurut H.L.A. Hart, hukum tidak pernah sepenuhnya tertutup; selalu ada ruang interpretasi kelembagaan.
Kekosongan teknis tidak boleh dijadikan alasan untuk lumpuh. DPRD justru dituntut menggunakan diskresi konstitusionalnya sepanjang bertujuan menegakkan kewenangan yang sah.
Keputusan Paripurna sebagai Jalan Konstitusional
Dalam situasi ini, langkah paling rasional dan sah adalah keputusan politik-hukum melalui rapat paripurna. Paripurna dapat:
1. Menyatakan secara resmi bahwa pihak yang mangkir telah menghambat fungsi pengawasan DPRD
2. Menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik
3. Merekomendasikan pelaporan kepada aparat penegak hukum
4. Mengusulkan evaluasi hingga pencabutan izin usaha kepada pemerintah yang berwenang
Dalam teori regulatory governance, kepatuhan terhadap pengawasan adalah syarat keberlanjutan izin. Korporasi yang menolak diawasi sesungguhnya sedang menggugurkan legitimasi administratifnya sendiri.
Jika DPRD Diam, Negara yang Kalah
DPRD memang tidak mencabut izin secara langsung. Namun rekomendasinya memiliki daya ikat politik dan moral hukum. Jika DPRD memilih diam, maka yang runtuh bukan hanya kewibawaan lembaga perwakilan, tetapi juga arsitektur negara hukum di daerah.
Negara tidak boleh kalah oleh dalih “aturan internal perusahaan”. Sebab sejak izin diterbitkan, perusahaan telah memasuki wilayah hukum publik dan wajib tunduk pada mekanisme pengawasan demokratis.
Pertanyaannya kini bukan lagi apakah DPRD dihina, melainkan: apakah DPRD bersedia membiarkan kewenangannya dilecehkan? ***