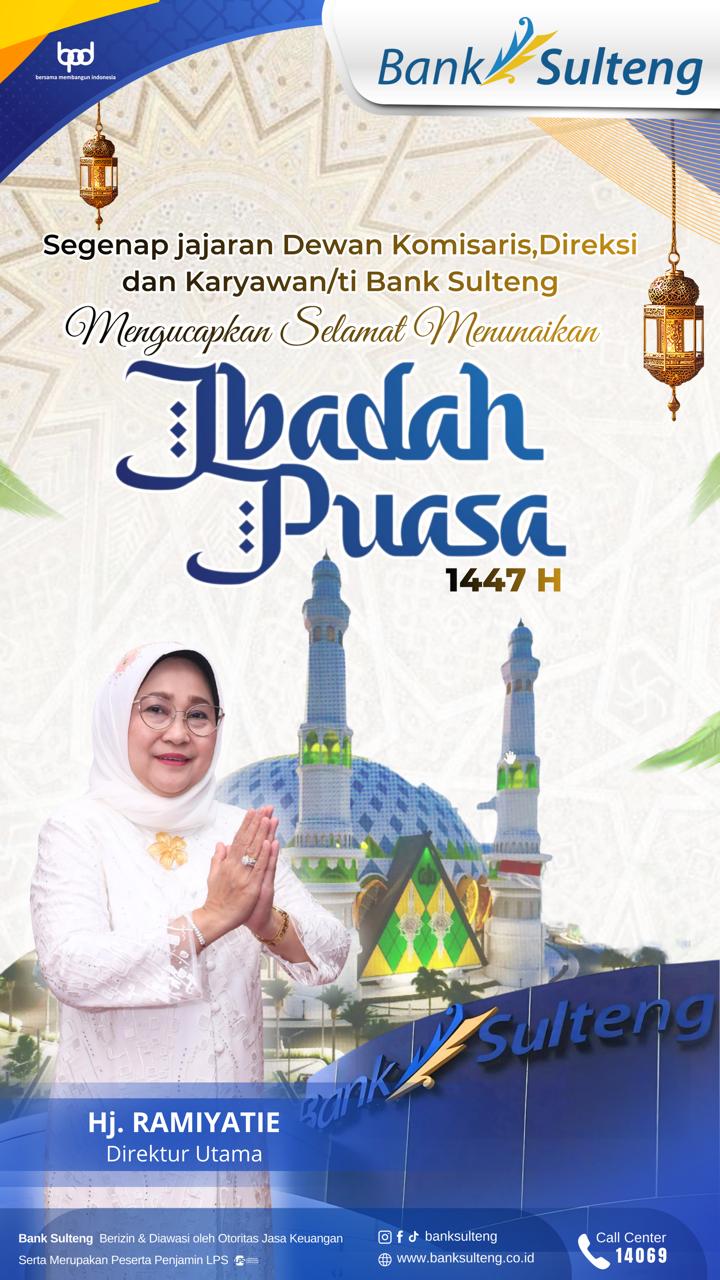Jakarta,- Hasyim Asy’ari selaku ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), mengungkapkan bahwa ada tiga aspek terkait aturan pelarangan mantan napi korupsi mengikuti pencalonan legislatif (caleg). Yaitu, aspek filosofis, aspek hukum yuridis dan aspek sosiologis.
Hal tersebut disampaikan Hasyim dalam acara Rakornas Sentra Gakkumdu Dialog Interaktif yang disiarkan di YouTube Bawaslu, Selasa (20/9/2022).
“Jadi secara filosofis misalkan, mengapa KPU merumuskan mantan napi korupsi) enggak boleh nyaleg. Secara filosofis jelas, kita ingin pemimpin yang dapat diteladani, karena kepemimpinan yang sesungguhnya adalah keteladanan. Kalau ada pemimpin ngomong ini itu, ini itu, tapi kelakuannya seperti yang diomongkan orang, sudah tidak percaya. Padahal diperlukan sebuah kepercayaan dalam kepemimpinan,” kata Hasyim.
“Oleh karena itu karakter orang yang bersih, yang tidak pernah terlibat pidana menjadi sesuatu yang penting, filosofinya begitu,” Tambahnya.
Kemudian, Hasyim menjelaskan aspek kedua, ialah aspek yuridis. Dia menyebut saat ini TAP MPR mengenai penyelenggara pemilu yang bersih dan bebas KKN masih berlaku.
“Yang kedua, aspek yuridis. Saya kira kita tau semua TAP MPR tentang penyelenggara yang bersih dan bebas KKN masih berlaku. Itu sebuah antitesa dari situasi masa lalu yang dianggap korup,” katanya.
Hasyim mengatakan dalam UU Pemilu, untuk menjadi calon presiden (capres) dan calon legislatif ialah tidak pernah terjerat pidana. Menurutnya, tujuan pemilu adalah untuk membentuk pemerintahan.
“Kalau eksekutif ya presiden dan legislatifnya DPR, capres dituntut bersih, maka kita bisa memaknai mestinya calon anggota DPR juga bersih supaya kemudian pemerintah di atasnya juga bersih. Ini yang saya maksud dengan penafsiran yuridis, penafsiran sistematis, yang tidak hanya bertumpu pada pemilu tapi membaca berbagai macam aturan yang berkaitan dengan mengisi jabatan bernegara,” katanya.
Lebih lanjut, Hasyim menjelaskan aspek ketiga ialah aspek sosiologis. Menurutnya, jika mantan koruptor menjadi caleg, akan menimbulkan keresahan pada sejumlah pihak.
“Arti sosiologis, pada waktu Pilkada 2018, pencalonannya itu dari tanggal 8-10 Januari 2018, kemudian setelah penetapan calon, tidak lama dari situ, ada sejumlah calon kepala daerah ditetapkan jadi tersangka dan kemudian ditahan. Inikan kemudian menimbulkan keresahan beberapa pihak,” katanya.
Hasyim kemudian menyinggung Pilkada tahun 2018 lalu. Pada saat itu ada 2 kepala daerah yang menang pemilu tetapi juga ditahan karena kasus pidana.
“Yang pertama partai politik, mereka pada bertanya ke KPU, ‘mas sesungguhnya kalau ada calon kena pidana, statusnya tersangka lalu ditahan, boleh diganti nggak? Karena kami ya malu mau meneruskan pencalonan ini, bisa jadi profil partai kami jadi menurun karena calonnya kena masalah’. Lalu teman-teman masyarakat sipil, organisasi kemasyarakatan juga bertanya, ‘mas bisa diganti nggak? Kita kan mau punya calon yang seperti ini’,” sambungnya.
“Dan faktanya setelah coblosan, 27 Juni 2018, ada dua tempat calon kepala daerah yang sudah ditahan, menang dalam Pilkada Tulung Agung dan Provinsi Maluku Utara. Pertanyaannya, apakah dengan begitu Pilkada tercapai, kalau yang terpilih adalah orang yang sudah kena persoalan hukum? Jawabannya jelas tujuan pilkadanya tidak tercapai karena yang terpilih adalah orang yang kena menyandang di kantor-kantor penegak hukum. Secara sosiologis seperti itu,” tuturnya. ***
ED/Sumber: RK/detik.com